Banjir, Perubahan Iklim, dan Impian Anak-anak yang Terancam
- firdausdanoe
- 10 Feb 2025
- 5 menit membaca
Banjir
Banjir merupakan masalah yang sering terjadi di banyak kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Penyebab utamanya adalah kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Curah hujan yang tinggi, terutama saat musim penghujan, diperparah oleh buruknya sistem drainase dan tingginya laju urbanisasi. Alih fungsi lahan hijau menjadi permukiman dan area komersial mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air, sehingga air hujan langsung mengalir ke permukaan dan membanjiri jalan-jalan serta permukiman.

Dampak banjir di perkotaan sangat luas, mulai dari kerugian material hingga gangguan sosial dan ekonomi. Ribuan rumah terendam, aktivitas warga terganggu, dan akses transportasi menjadi lumpuh. Banjir juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, seperti kerusakan infrastruktur, penurunan produktivitas, dan biaya pemulihan yang tinggi. Tidak hanya itu, banjir juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit, seperti diare dan leptospirosis, yang membahayakan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya terintegrasi, seperti perbaikan sistem drainase, penegakan regulasi tata ruang, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.
Perubahan Iklim
Berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada tahun 2013, dalam satu abad terakhir terjadi percepatan pemanasan global akibat meningkatnya produksi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang berasal dari penggunaan bahan bakar fosil serta aktivitas manusia, seperti perubahan lahan dan deforestasi (IRID, 2021). Berdasarkan data World Resources Institute (WRI), suhu rata-rata bumi telah meningkat sekitar 0,8⁰C sejak tahun 1880. Jika suhu naik di atas 1,5⁰C dampaknya akan semakin parah dan jika suhu terus meningkat dengan laju seperti ini maka pemanasan global kemungkinan akan mencapai 1,5⁰C pada rentang tahun 2030 hingga 2052.
Kota Tangguh
Kota tangguh atau resilient city adalah kota yang mampu beradaptasi, bersiap, dan memulihkan diri dari bencana yang mengancam. Konsep kota tangguh dapat diwujudkan tidak hanya dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum saja, tetapi juga kesiapan sosial masyarakat dalam melakukan upaya mitigasi dan pemulihan ketika terjadi bencana.
Contohnya adalah ketika sedang musim kemarau panjang dan terjadi kelangkaan air bersih, pemerintah memperluas jaringan perpipaan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses air bersih. Selain itu untuk mengantisipasi terjadinya banjir, pemerintah melaksanakan program-program untuk membersihkan sampah dari sungai, mengeruk endapan lumpur di sungai, melakukan perbaikan saluran drainase, dan langkah-langkah lainnya untuk mengurangi dampak apabila terjadi banjir. Masyarakat kota juga dapat turut berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan mulai dari di sekitar tempat tinggal.
Dampak Nyata
Dampak-dampak perubahan iklim secara nyata sudah terasa, bukan hanya di kawasan pesisir tetapi juga di permukiman kota. Di kawasan pesisir terdapat intrusi air laut dan penurunan muka tanah atau land subsidence (Darmawardana, 2024). Kelangkaan air bersih di sejumlah daerah juga menjadi salah satu permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Pada tahun 2023 Indonesia merupakan negara dengan cakupan air minum perpipaan terendah di ASEAN dengan persentase hanya 19,47%, jauh di bawah capaian Thailand dengan 71% atau bahkan Malaysia dan Singapura dengan capaian masing-masing 95% dan 100%. Dampaknya, masih banyak penduduk yang harus memenuhi kebutuhan air bersihnya dengan membeli air bersih eceran dengan harga yang jauh lebih mahal.
Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin, dan kelembaban yang menyebabkan terjadinya kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, maupun gelombang panas. Bencana hidrometeorologi erat kaitannya dengan perubahan iklim. Di kawasan perkotaan, bencana yang paling sering terjadi di Indonesia adalah banjir ketika curah hujan yang tinggi tidak diimbangi dengan kapasitas saluran drainase yang cukup.
Membangun Permukiman Tangguh Bencana
Dampak-dampak yang nyata di kawasan pesisir akibat perubahan iklim perlu disikapi dengan berbagai pendekatan termasuk sosial budaya masyarakat perkotaan, tidak hanya pendekatan infrastruktur fisik saja. Infrastruktur besar seperti tanggul laut sering kali diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi kawasan pesisir Jakarta yang diprediksikan akan semakin tenggelam. Pendekatan infrastruktur harus mempertimbangkan dan mengakui keberadaan aspek budaya masyarakat yang terkena dampak, serta mengadopsinya ke dalam solusi final yang dijalankan (Pristine & Sutanudjaja, 2024).
Sementara itu di Kampung Glintung Kelurahan Purwantoro Kota Malang dahulu merupakan daerah langganan banjir, berinovasi melahirkan gerakan menabung air atau meresapkan air hujan kembali ke tanah dengan dengan membangun 7 sumur resapan dan 1.100 lubang biopori secara swadaya oleh masyarakat. Selama tiga tahun program ini berjalan sumur-sumur warga naik 5 meter dan suhu udara di kampung menjadi turun. Penerapan sistem drainase berwawasan lingkungan atau disebut eko-drainase seperti ini dibutuhkan di permukiman kota, untuk melengkapi sistem drainase konvensional. Prinsip dari eko-drainase yang meminimalisir terbuangnya air hujan sebagai aliran permukaan dengan agar meresapkan kembali ke tanah dapat diaplikasikan melalui kolam retensi, sumur resapan, maupun lubang biopori yang dapat dikerjakan secara swadaya skala kecil oleh masyarakat (Riduan et al, 2024).
Impian Anak yang Terancam
Perubahan iklim adalah ancaman terbesar yang dihadapi anak-anak dan generasi muda di dunia. Indeks Risiko Iklim Anak-anak UNICEF mengungkapkan bahwa 1 miliar anak berada pada risiko yang sangat tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Jumlah tersebut hampir setengah dari seluruh anak-anak. Dan itu sedang terjadi hari ini (Unicef, 2021).

Sebanyak 920 juta anak (lebih dari sepertiga anak-anak di seluruh dunia) saat ini sangat rentan terhadap kelangkaan air. Hal ini kemungkinan akan menjadi lebih buruk karena perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan kekeringan, kekurangan air, peningkatan permintaan dan persaingan terhadap air, yang mengakibatkan menipisnya sumber daya air yang tersedia.
Selain itu, 330 juta anak (1 dari 7 anak di seluruh dunia) saat ini sangat rentan terhadap banjir sungai. Hal ini kemungkinan akan memburuk seiring dengan mencairnya gletser dan meningkatnya curah hujan akibat tingginya kandungan air di atmosfer akibat suhu rata-rata yang lebih tinggi.
Anak-anak lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim dan krisis ekologi dibandingkan orang dewasa karena anak-anak lebih lemah secara fisik, psikologis, memiliki risiko kematian yang lebih tinggi apabila terserang penyakit karena krisis iklim, seperti DBD atau malaria.
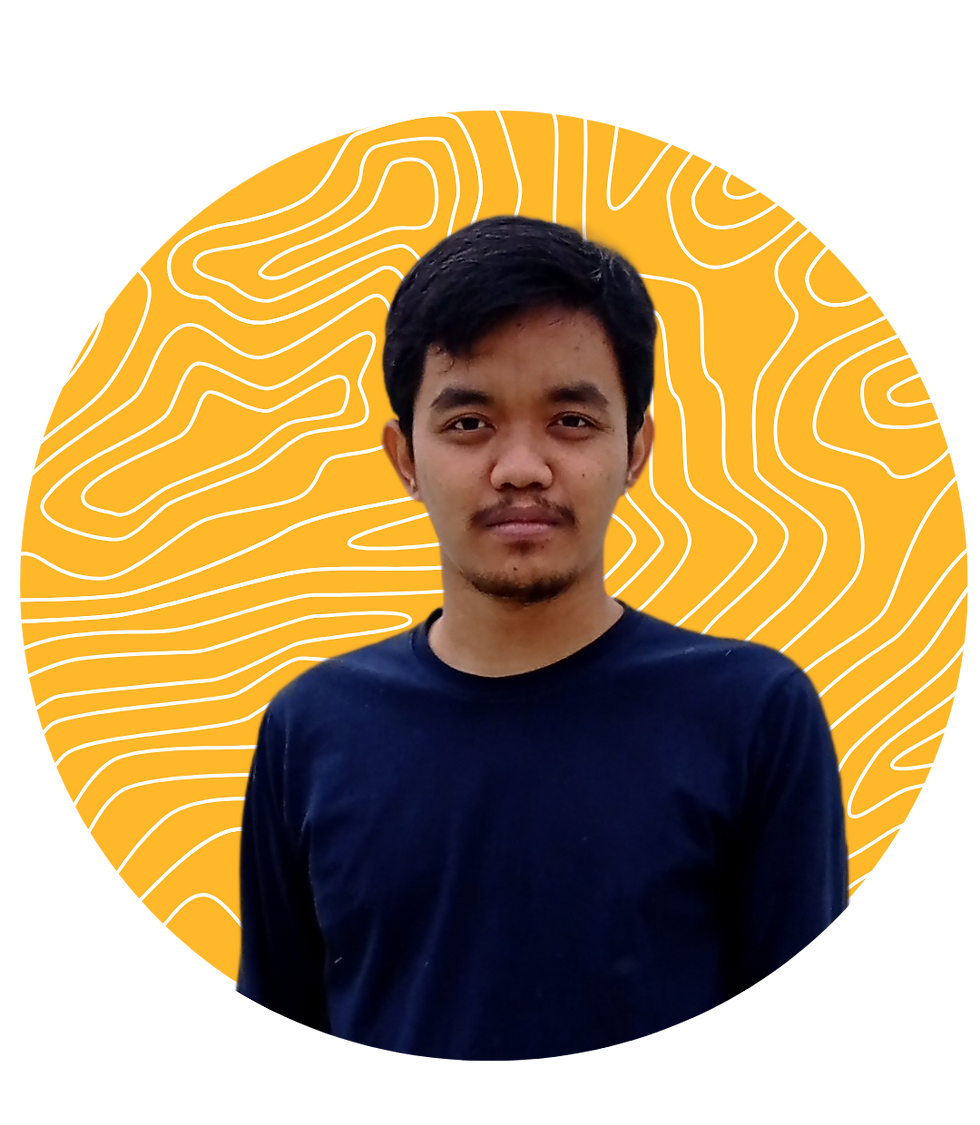
"Perubahan iklim memiliki dampak jangka panjang untuk masa depan anak-anak. Pemerintah dan semua stakeholder perlu berkolaborasi untuk merancang kebijakan-kebijakan untuk menciptakan kota yang lebih tangguh dan ramah lingkungan. Kebijakan di tingkat nasional dan daerah perlu diselaraskan dengan kebutuhan masa depan anak-anak dan generasi muda untuk membawa perubahan nyata bagi lingkungan. Mari dimulai dari hal kecil, seperti menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, dan mendukung kebijakan yang berkelanjutan. Impian anak-anak untuk hidup di dunia yang aman dan nyaman tidak boleh pupus."
Korespondensi Penulis
Yusuf Maulana AK /yusufkariem@gmail.com
Daftar Literatur
Darmawardana, D. (2024). Kota dan Krisis Iklim: Cerita Air dari Pesisir. Rujak Center for Urban Studies. https://rujak.org/kota-dan-krisis-iklim-cerita-air-dari-pesisir/ (diakses tanggal 4 Februari 2025)
IRID (2021). Mengenal Perubahan Iklim. Indonesia Research Institute for Decarbonization.
Pristine, Sutanudjaja. (2024). Adapting to the Sinking City: Collectivism, Belief, and Identity. A Case Study of Coastal Kampung Communities in North Jakarta, Indonesia.
Riduan et al. (2024). Perencanaan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan (Eko-Drainase) di Kecamatan Banjarbaru Utara. Jurnal Ilmu Lingkungan Vol 22 Issue 4 (2024): 987-995.
Unicef. (2021). The Climate Crisis is a Child Rights Crisis, Introducing the Children’s Climate Risk Index.
WRI Indonesia. Buklet Keberlanjutan: Seri 1 Krisis Iklim. https://wri-indonesia.org/sites/default/files/WRI%20Buklet%20Berkelanjutan%20-%2001%20Krisis%20Iklim.pdf (diakses tanggal 4 Februari 2025)




Komentar